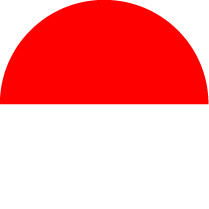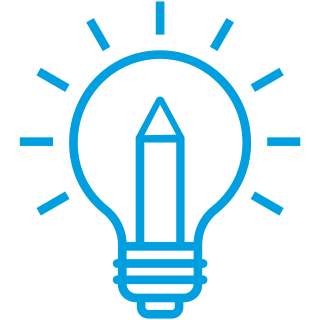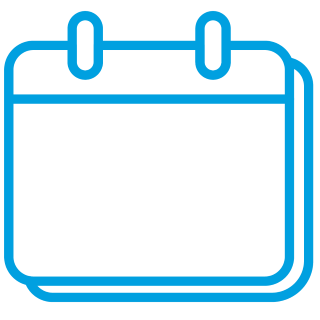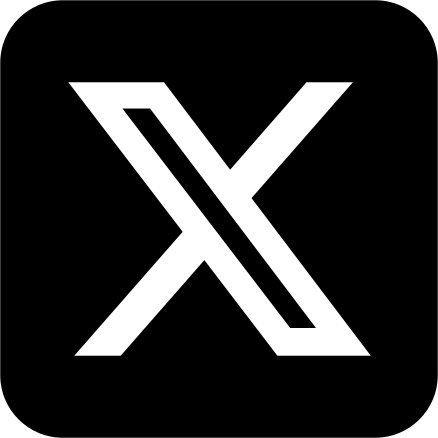"Perjalanan adalah ruang belajar yang mahabesar. Ia tak hanya mengajarkan pengetahuan,
tetapi juga kearifan dan kebajikan. Dan saya, saya adalah murid yang tidak pernah akan lulus."
***
JALANAN menuju Machupicchu yang sedang saya tapaki entah mengapa tak terasa terlalu berat dibandingkan ketika berada di Pulau Taquile, Puno, Peru. Di pulau yang serupa titik kecil di tengah Danau Titicaca dan berhadap-hadapan dengan daratan Bolivia itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, saya ingin menyerah di tengah perjalanan. Saya dan Riyanni Djangkaru terserang mabuk gunung atau penyakit ketinggian (altitude sickness) karena tidak melakukan aklimatisasi secara layak. Kami akan menuju ke titik tertinggi pulau tersebut, berada di 4050 meter di atas permukaan laut. Titik ini jauh lebih tinggi daripada Machupicchu. Daun koka yang kami konsumsi tidak menolong sama sekali. Selain kepala pusing luar biasa dan tubuh yang lunglai, napas kami pun sepotong-sepotong. Saya menatapi Riyanni yang berjalan lambat di belakang saya dan diam tak bersuara. Kondisi saya bisa dibilang sedikit lebih baik dari Riyanni, meskipun setengah mati saya berusaha keras melawan sakit yang menusuk-nusuk kepala.
‘Berapa jauh lagi?’ Saya bertanya kepada pemandu yang tak juga bisa kami ingat namanya. Ia suku Quechua. ‘Jalan pelan-pelan saja,’ katanya. Itu sama sekali tak menjawab pertanyaan saya. ‘Kalau seandainya saya tidak sanggup naik, saya bisa menunggu di mana?’ Riyanni bertanya. Saya mengamati kawan seperjalanan saya. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah, saya mendengar hal itu keluar dari mulutnya. Ia selalu jadi orang yang bersemangat dan menyemangati. Sadar saya menatapinya, ia berkata, ‘Tidak sampai atas tidak apa-apa, kan?’ Saya mengangguk. Perjalanan telah mengajarkan kami soal mengenali batas diri.
‘Kalau nggak kuat dan mau turun bilang, ya.’ Saya berkata sambil menyodorkan butir cokelat ke Riyanni. Dari yang saya baca, ini bisa membantu. Koka tidak mempan, siapa tahu cokelat lebih mujarab.
‘Pelan-pelan saja.’ Ia menjejeri langkah saya dan meminta saya mengulurkan tangan kepadanya. Ditekan-tekannya area bantalan di bawah ibu jari sambil berkata, ‘Walk slowly, drink a lot of water, and remember it is not a competition.’
Wajah saya meringis menahan sakit. Tekanannya di area di antara ibu jari dan telunjuk terasa seperti mengantarkan hantaman di kepala. Sesaat pening menghilang. Katanya ini membuka laju jalan oksigen ke kepala saya. Sambil terus memijat, ia berkata, ‘Today is a special day, only happens once in a year. And you’re here. But if you couldn’t make it, it’s okay. You and your friend come back to the boat and take a rest. Wait for us. Remember, this journey is not a competition.’
Saya dan Riyanni saling melempar pandang tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Berkawan dan telah berkali-kali melakukan perjalanan bersama, kami berdua mengenali karakter masing-masing. Ambisi kami tak lagi sama seperti dulu. Semakin kerap berjalan, kami semakin sadar bahwa perjalanan bukan soal cap di paspor atau foto-foto cantik yang menunjukkan kami berada di mana. Ke Peru adalah soal menjawab rasa penasaran dan mencari tahu. Tanpa terbebani kami berjalan pelan. Berhenti di mana saja kami mau sambil melontarkan becandaan yang sama sekali tidak lucu. Anehnya, kami bisa tertawa-tawa saja. Saya ingat, saya bernyanyi-nyanyi kecil sambil menunjuk dataran Bolivia. ‘Itu lihat ada titik jauh di tengah lauuuut~ Boliviaaa oh Boliviaaaaa….’ Tentu jangan ditanya nadanya. Dalam kondisi waras pun saya buta nada, apalagi dalam kondisi diserang mabuk gunung.
Lalu tibalah kami di sana. Di titik tertinggi Pulau Taquile, tepat di tengah alun-alun desa. Sebenarnya, pemandu kami sendiri pun tak tahu kalau hari itu adalah hari perayaan kelahiran Pulau Taquile. Seluruh penduduk desa dari semua suku yang tinggal di pulau menyemut di alun-alun, berparade dengan pakaian tradisional mereka. ‘Ini harga untuk perjuanganmu,’ kata pemandu ketika menyambut saya tiba di atas. Ia tersenyum bangga. ‘Tak semua orang yang datang ke sini berkesempatan menyaksikan apa yang ada di depan matamu sekarang.’
Pusing saya tidak hilang, melainkan teralihkan dengan semaraknya parade. Mama-mama dalam pakaian tradisional terbaik mereka. Para lelaki yang mengayunkan panji-panji dan menabuh alat musik. Anak-anak yang pipinya seperti apel ranum—memerah terbakar matahari, berlarian gembira dalam pakaian yang menunjukkan identitas kesukuan. Saya tersenyum kecil, menepuk pundak sendiri karena bangga telah mampu mencapai apa yang awalnya saya pikir tidak akan sanggup saya gapai, lalu menyeret kaki dan badan yang setengah limbung untuk berbaur di kerumunan. Dengan sisa kekuatan, saya berusaha mengambil foto tanpa peduli urusan komposisi, fokus-tidak fokus, dan ini-itu. Foto buruk sekali pun jauh lebih baik daripada tak ada sama sekali dokumentasi untuk perayaan yang hanya bisa dilihat setahun sekali ini.
Ketika kami akhirnya turun, satu hal saya pahami lagi. Perjalanan memang membuat saya mengetahui batas diri, termasuk melampauinya untuk menemukan sempadan baru.
***
‘KIRI kalian ada ular!’ kata Peter, pemandu saya dan Riyanni, tak lama setelah gerbang Machupicchu kami lewati. Bukannya menyingkir, Riyanni dan saya malah mengawaskan mata. Mencari bentuk hewan melata yang dimaksud Peter. ‘Kalian tidak takut?’
Serempak kami menggeleng. Saya suka ular. Riyanni malah tergila-gila kepada ular. ‘Wah, ini pertanda baik. Belum apa-apa, kalian sudah disambut penghuni Machupicchu,’ sahut Peter. Riyanni sibuk memotret. Saya hanya berdiri melihat bagaimana hewan itu bergerak melata di pinggiran jalan setapak menuju ke titik di mana orang-orang berhenti untuk mengagumi citadel Machupicchu. Kalau dalam istilah Peter, titik untuk foto editoral majalah National Geographic.

Meneruskan perjalanan tanpa terseok seperti di Puno, saya dan Riyanni bisa lebih jeli melihat apa yang ada di sekitar kami. Dua orang dari Jepang yang awalnya bergabung dengan kami berpisah. Mereka hendak lanjut ke The Sun Gate, setelah itu turun ke citadel. Saya dan Riyanni hari itu memutuskan ‘memeras’ otak Peter soal Machupicchu. Peter adalah asli Inca dan seorang sejarahwan. Ia menamatkan pendidikannya di sebuah universitas di Cusco. Di Peru, terutama di Machupicchu, kata Peter, pemandu harus memiliki pengetahuan cukup soal sejarah Peru dan Inca. Semakin kami mendekati Machupicchu dan mendengar cerita Peter soal peradaban kuno Inca, semakin kami menyadari bahwa tidak semua cerita dan misteri tentang Machupicchu telah terjawab. Inca tahu banyak orang mencari kota kunonya yang hilang dan ingin menyaksikan kemegahan peradabannya yang konon melampaui nalar pengetahuan manusia. Machupicchu hanya menunjukkan sedikit dari kemajuan peradabannya itu. ‘Tempat ini ditemukan karena nenek moyang kami membuat ini ditemukan, bukan karena Hiram Bingham berhasil menemukan,’ cerita Peter selagi kami menatap citadel Machupicchu yang berada di Lembah Urubamba. Kabut tipis perlahan mengangkasa seiring dengan sinar matahari dari arah The Sun Gate jatuh tepat di apa yang diyakini dunia sebagai kota kuno Inca.
Padahal satu dunia ditipu Inca. Machupicchu bukan kota suci Inca yang dicari semua penjelajah. Bingham tergesa-gesa mengumumkan kepada dunia bahwa perjalanannya berbuah hasil. Ia adalah orang yang berhasil menemukan kota kerajaan Inca yang hilang akibat perang, yaitu Vilcabamba. ketergesa-gesaannya ini, kata Peter, didorong oleh beban mental agar ekspedisi pencarian Kota Inca yang Hilang tidak terkesan gagal. Bagaimana tidak, dana yang digelontorkan untuk Bingham sangat besar. Butuh waktu 50 tahun untuk Bingham mengakui kebenaran bahwa Machupicchu bukanlah Vilcabamba—Kota Suci Inca yang sesungguhnya. Itu pun dilakukan Bingham setelah seorang penjelajah bernama Gene Savoy membuktikan bahwa kota Inca yang hilang tidak berlokasi di lembah ini.

Namun, dunia terlanjur terpukau dengan Machupicchu. 400 tahun tak diketahui keberadaannya, kota Inca ini masih utuh dengan 60% struktur utama berada di bawah tanah. Arsitektur yang belum mampu dijelaskan oleh akal sehat, serta sistem irigasi pertanian yang sangat modern, tetapi berbasis pada perputaran alam, termasuk ilmu perbintangan. ‘Kota Keliru’ inilah yang membuka mata dunia tentang peradaban Inca. menariknya lagi, Machupicchu adalah salah satu kota Inca yang tak pernah ditemukan dan ditundukkan Spanyol.
‘Bisa jadi, nenek moyangku pun hanya bersiasat agar kota suci utama kami tidak ditemukan dengan menyodorkan Machupicchu kepada Bingham.’ Sebuah analisis dilontarkan Peter. ‘Tak ada yang tahu, kan?’
Dunia benar-benar ditipu. Namun, ini penipuan yang membuka sedikit pengetahuan soal kemajuan peradaban Inca. Semaju-majunya peradaban adalah ia yang mampu membangun dan bertumbuh bersama alam tanpa kehilangan akar leluhurnya bukan?
Saya dan Riyanni tercenung-cenung mendengar perkataan Peter. Kami telah menunggu lama dan rela mengitari separuh bola dunia demi mengenyangkan rasa ingin tahu atas peradaban manusia. Perjalanan buat kami bukan lagi soal seberapa jauh, melainkan seberapa lapang kami sanggup membuka diri untuk bertemu banyak ketidaktahuan dan tekun memunguti jawabannya.
Buat saya, Machupicchu adalah Pachamama (Ibu Bumi dalam bahasa Quechua) yang mistis. Yang hari itu mengingatkan saya bahwa perjalanan tidak hanya menyuguhkan jawaban dari rasa ingin tahu, tetapi juga terus menjagakan rasa lapar kita atas pengetahuan. Layaknya seorang ibu, ia tahu bahwa untuk membuat anak-anaknya bertumbuh dan sanggup membangun peradaban yang lebih berkembang, maka rasa ingin tahu inilah yang harus terus dipelihara. Dan jawaban hanya disediakan bagi mereka yang mencari tahu, bahkan lewat sebuah perjalanan.
***
MATA pelajaran saya di kelas bernama ‘Perjalanan’ ini sungguh lengkap. Sejujurnya, kesadaran finansial dalam diri pun muncul berkat perjalanan.
Di perjalanan, saya belajar mengatur keuangan. Saya menjadi peka dalam mengendalikan pengeluaran di perjalanan, termasuk memilih produk perbankan yang menawarkan keuntungan lebih berkaitan kesukaan saya melakukan perjalanan dan juga memberikan kenyamanan selama di perjalanan.
Sewaktu akan melakukan perjalanan ke Peru, rute penerbangan yang kami pilih melewati jalur selatan. Rute ini, selain membuat saya melakukan penerbangan panjang melintasi Samudra Pasifik—nyaris 38 jam—juga membuat saya harus transit di bandara-bandara yang berbeda negara.
Karena sangat menyukai bandara, buat saya melakukan penerbangan panjang yang memungkinkan singgah di banyak bandara adalah salah satu bentuk #jalan2jenius. Namun, ini juga membuat saya menjadi lebih cermat dalam urusan keuangan. Bermain banyak mata uang bisa sangat merepotkan, apalagi kalau kebutuhannya hanya untuk selama singgah beberapa jam. Kadang-kadang, kita tidak menyadari, salah satu sumber pemborosan di perjalanan terjadi ketika melakukan konversi berkali-kali ke beberapa mata uang. Belum lagi uang yang pecah (mata uang kecil, terutama koin) biasanya tidak bisa dipakai bertransaksi di luar negara tersebut karena tidak ada nilai tukarnya. Akhirnya, hanya tersisa dua pilihan: dihabisin atau jadi koleksi.
Untuk menghindari hal-hal seperti ini, saya memilih melakukan transaksi apa pun secara cashless. Bisa dengan kartu kredit atau menggunakan kartu debit yang cerdas, seperti Kartu Debit Jenius Visa. Selain tidak diribetkan dengan urusan tukar uang, fasilitas Visa Contactless-nya membuat proses transaksi selama berpindah bandara dan negara menjadi mudah sekali. Tinggal tempel atau gesek dan beres.
Selain mengamati kemudahan bertransaksi, saya mengamati nilai tukar yang diberikan setiap bank. Ada banyak bank menawarkan fasilitas untuk perjalanan, tetapi mengenakan nilai tukar yang tidak kompetitif dan potongan penarikan yang sangat tinggi. Cermat mengatur keuangan buat saya bisa dimulai dari memilih produk keuangan/perbankan yang tepat untuk dijadian ‘kawan jalan’.
***
BERSIAPLAH. Sekali kita menemukan kesenangan dalam perjalanan, ia lantas menjelma candu. ‘Kawan Jalan’ yang tepat akan sanggup membawa kita berjalan lebih jauh dan lebih lama. Itu mengapa, saya tidak pernah akan lulus dari kelas ini.